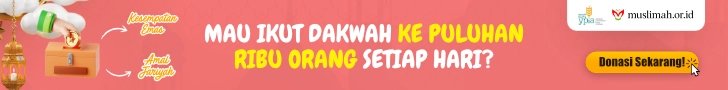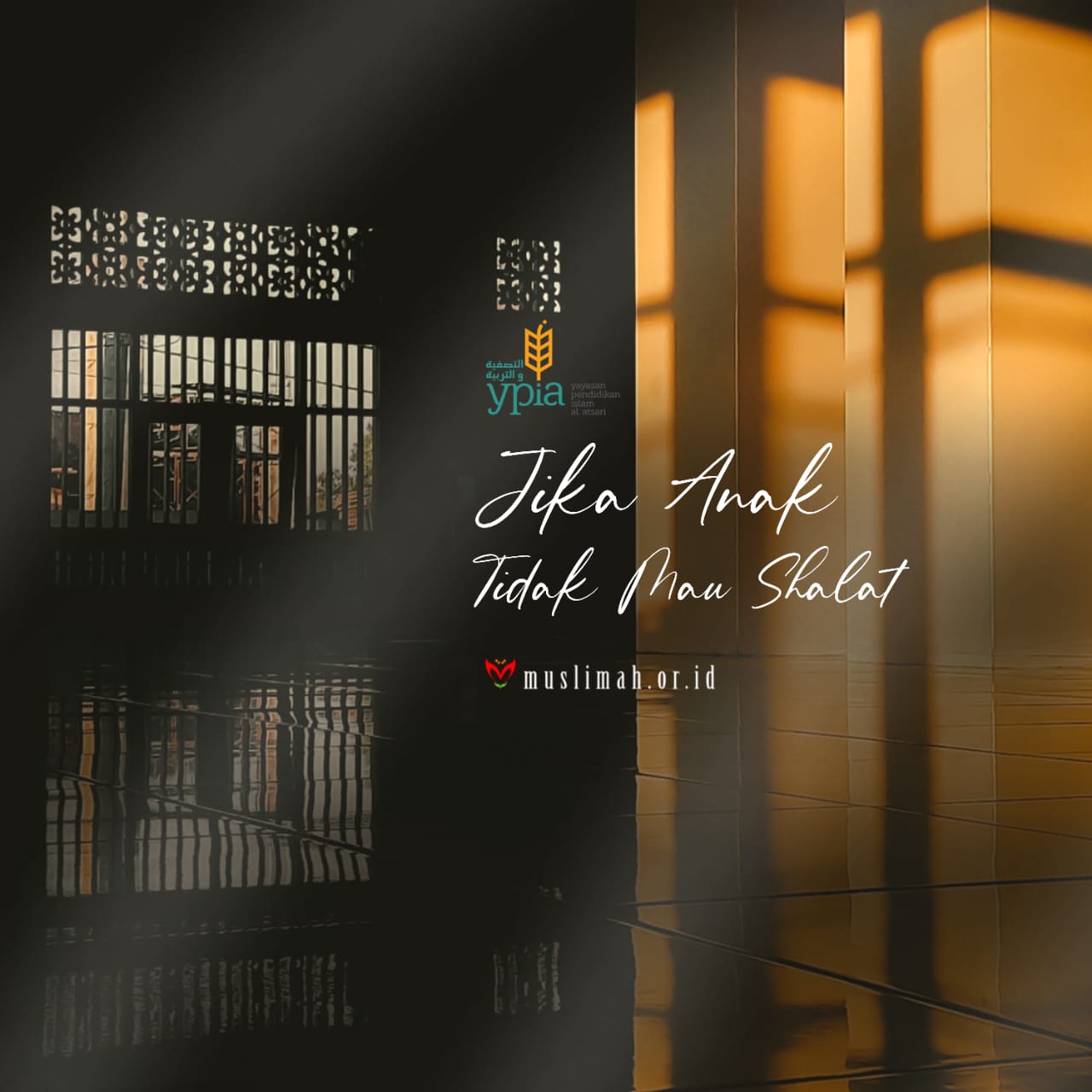Pada pertengahan tahun 2022, Indonesia dihebohkan dengan kasus seorang polisi yang dipaksa membunuh rekannya oleh atasannya. Alhasil, pada tahun 2023, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada atasannya tersebut , yang berubah menjadi hukuman seumur hidup. Sedangkan polisi yang membunuh secara langsung dikenai hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Bagaimana hukum Islam dalam menghadapi kasus seperti ini?
Konsekuensi membunuh
Pembunuhan bisa terjadi karena tiga sebab: 1) sengaja, 2) tidak sengaja, dan 3) “semi” sengaja
Sengaja: Orang tersebut benar-benar bermaksud membunuh dan dengan menggunakan alat yang sudah diketahui secara umum bahwa alat tersebut bisa membunuh seseorang, misalnyasenjata tajam, senjata api, dan sejenisnya. Jika hal tersebut menyebabkan kematian atau menyebabkan sebagian tubuh terluka, maka wajib diqishash
Tidak sengaja: Orang tersebut melakukan pembunuhan, tanpa maksud ingin membunuh. Baik ditinjau dari perbuatannya (perbuatannya tidak dimaksudkan untuk membunuh, misalnya main-main melempar batu, tapi ternyata di seberang sana ada orang dan terkena orang tersebut, lalu meninggal) ataupun target yang ingin dibunuh.
Semi sengaja: Orang yang menggunakan suatu alat yang diketahui secara umum bahwa alat tersebut tidak dapat membunuh seseorang, namun dia membunuh seseorang dengan alat tersebut. Misalnya,memukul dengan tongkat yang ringan, namun korban meninggal dunia.
Dari sini, kita mengetahui bahwa membunuh seseorang dengan menggunakan senjata api, semisal pistol merupakan pembunuhan sengaja, dan berkonsekuensi qishash. (Umdatus Salik, hal. 423)
Bagaimana jika dipaksa?
Ikrah (الإكراه) (pemaksaan) adalah ketika seseorang harus melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan hal yang haram, maka tidak ada dosa baginya. Seperti orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran, sedangkan hatinya tetap mantap dengan iman, maka tidak ada kewajiban apa-apa untuknya. Orang yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, maka tidak ada kewajiban apa-apa untuknya ketika dia sedang dipaksa. Namun ketika paksaan itu sudah hilang, maka dia wajib meng–qadha kewajibannya tersebut. Seperti orang yang meninggalkan salat karena dipaksa hingga waktunya berakhir, maka dia wajib meng–qadha salatnya tersebut ketika paksaan tersebut sudah hilang. Pemaksaan ini hanya menjadi penghalang taklif terhadap hak Allah, karena hak Allah dibangun di atas pemakluman dan kasih sayang. Adapun terhadap hak makhluk, maka tidak ada penghalang dari tanggungan (baca: ganti rugi) jika dia memiliki kewajiban menanggung sesuatu yang berkaitan dengan hak orang lain dan orang lain tersebut tidak rida jika tanggungan tersebut digugurkan. Allahu a’lam. (Ushul min Ilmin Ushul, hal. 25-26)
Karena pembunuhan itu berkaitan dengan hak manusia, maka ketika dipaksa, seseorang tetap wajib menanggung konsekuensi dari pembunuhan tersebut.
Orang yang melakukannya secara langsung lebih didahulukan daripada orang yang membuat sebab
Terdapat sebuah kaidah fikih yang berbunyi,
المباشر مقدم على المتسبب
Pelaku langsung lebih didahulukan daripada pembuat sebab.
Pelaku langsung adalah orang yang menghasilkan kerusakan tersebut karena perbuatannya secara langsung tanpa perantara (dalam hal ini adalah orang yang dipaksa membunuh orang lain), sedangkan pembuat sebab adalah orang yang menjadikan perbuatan tersebut terjadi, namun tidak melakukannya secara langsung (dalam hal ini adalah orang yang memaksa seseorang untuk membunuh orang lain).
Artinya, apabila terdapat pelaku langsung dan pembuat sebab yang menyebabkan perbuatan tersebut terjadi, maka hukum perbuatan tersebut tetap disandarkan kepada pelaku langsung, karena sebab yang menjadikan perbuatan tersebut terjadi adalah pelaku langsung. Pada dasarnya, hukum disandarkan kepada sebab langsung terjadinya suatu perbuatan, bukan pada sebab yang mendorong terjadinya perbuatan . Inilah pendapat yang lebih kuat.
Dalil dari kaidah ini adalah,
كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (QS. Al-Muddatstsir: 38)
Sisi pendalilannya, pelaku langsung adalah orang yang disandarkan kepada perbuatan tersebut secara hakiki, sehingga dia harus menanggung apa yang telah diperbuat. Sedangkan orang yang membuat sebab, dia juga bisa dikatakan pelaku, namun secara majaz. (Al-Jawahir Al-Adniyyah, hal. 48)
Dalam bab Ikrah (pemaksaan), seorang yang dipaksa tidak berdosa karena terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam,
إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
“Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku dari kekeliruan, lupa, dan sesuatu yang dia dipaksa atasnya.” (HR. Ibnu Majah)
Korban pemaksaan tetap tidak dimaafkan dalam dua hal
Namun, kaidah ini dikecualikan dalam dua hal.
Pertama: Pembunuhan jiwa yang terjaga darahnya (haram untuk dibunuh), melukai anggota badan, dan memotong salah satu dari alat gerak (kaki atau tangan). Ulama sepakat bahwa hal ini tetap tidak diperbolehkan, meskipun dipaksa, dan pelakunya berdosa. Adapun ulama berbeda pendapat tentang qishash-nya, apakah yang di-qishash adalah orang yang dipaksa atau orang yang memaksa. Namun, yang lebih tepat adalah orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tersebut, selaras dengan kaidah fiqhiyyah yang telah disebutkan sebelumnya.
Kedua: Ulama sepakat bahwa pemaksaan dalam hal zina tetap tidak diperbolehkan, orang yang zina karena terpaksa tetap mendapatkan dosa besar, meskipun ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum hadnya. Dan juga ada perbedaan apakah yang dipaksa itu laki-laki atau perempuan. Jika yang dipaksa adalah perempuan, maka ia tidak berdosa. Namun jika yang dipaksa adalah laki-laki, dan kemudian dia melakukannya, maka dia berdosa. Karena zina tersebut tidak akan terjadi tanpa ada ikhtiar darinya, dan jima’tidak terjadi tanpa adanya syahwat dan sentuhan. Maka zina itu terjadi karena kepatuhan dan kemauan dirinya terhadap orang yang memaksa. (Ushul Fiqh, hal. 91)
Allahu a’lam.
Baca juga: Untukmu yang Ingin Mengakhiri Hidup
***
Penulis: Triani Pradinaputri
Artikel Muslimah.or.id
Referensi:
- Al-Mishri, Ibnu Naqib. 1436 H. Umdatus Salik Wa Uddatun Nasik. Dar Ibnu Hazm. Beirut.
- Al-’Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 1422 H. Al–Ushul Min Ilmil Ushul. Darul Iman. Alexandria.
- As-Silmi, Iyadh Bin Nami. 1426 H. Ushul Fiqhi Al–Ladzi Laa Yasa’ul Faqiiha Jahluh. Darut Tadmuriyyah. Riyadh. Al-Maktabah Asy-Syamilah.
- Ghalib, Labib Najib Abdullah. 1440 H. Al–Jawahir Al–Adniyyah: Syarh Ad–Durrah Al–Qadimiyyah Nazhmu Al–Qawaid Al–Fiqhiyyah. Darushalih. Kairo.